Narasi Pagi – Di salah satu sudut Um Dawanban, wilayah di timur Khartoum, Mubarak Abdul-Salam berdiri di depan toko kecilnya, mencoba menata dekorasi sederhana berupa bulan sabit dan lampu warna-warni. Dekorasi itu dipasang bukan hanya untuk menyambut Ramadan, tetapi juga untuk membangkitkan kembali semangat yang hampir padam akibat perang yang masih berlangsung.
Sejak terpaksa meninggalkan rumahnya di Ed Hussein, Khartoum selatan, Abdul-Salam menetap di tempat baru ini dan membuka usaha kecil untuk bertahan hidup. Namun, di sekelilingnya, sisa-sisa pertempuran masih terlihat jelas. Bangunan yang hangus, tembok-tembok berlubang akibat peluru, serta jalan yang tertutup puing-puing menjadi saksi bisu dari pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF).
Meskipun kesedihan masih menghantui, ia berusaha menciptakan sedikit kebahagiaan dan mengingatkan orang-orang akan makna spiritual Ramadan. Namun, realitas di lapangan tidak mudah. Pelanggan yang datang semakin jarang, bukan hanya karena takut terhadap situasi keamanan yang tidak stabil, tetapi juga akibat harga barang yang meroket.
Sebungkus jawawut yang sebelumnya dapat dibeli dengan harga 40.000 pound Sudan, kini dijual seharga 200.000 pound. Hal yang sama terjadi pada jagung, yang harganya melonjak dari 30.000 pound menjadi 150.000 pound. Satu kilogram gula yang sebelumnya hanya 600 pound, kini harus dibeli dengan harga 2.500 pound. Sementara itu, minyak goreng yang dulu seharga 1.200 pound per liter kini mencapai 5.000 pound.
Kondisi ini semakin diperparah dengan melemahnya mata uang Sudan secara drastis. Nilai tukar satu dolar AS di pasar gelap kini mencapai 2.500 pound, meningkat tajam dari 580 pound sebelum konflik pecah pada April 2023.
Di Port Sudan, yang kini menjadi pusat perdagangan utama negara tersebut, suasana Ramadan juga terasa berbeda. Pasar-pasar yang biasanya ramai menjelang bulan suci kini sepi. Banyak toko yang tutup, dan yang masih beroperasi pun kesulitan mendapatkan barang untuk dijual.
Tradisi Ramadan yang selama bertahun-tahun dirayakan dengan semarak kini menghilang. Pemandangan dekorasi di etalase toko, prosesi berbagi makanan, hingga kehadiran kelompok penabuh gendang “Al Musaharati” yang biasanya membangunkan warga untuk sahur, kini tak lagi terlihat. Masalah keamanan serta penerapan jam malam membuat tradisi itu perlahan menghilang.
Khalid Hassan, seorang warga yang berusia 35 tahun, merasa bahwa Ramadan kali ini jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengaitkan perubahan tersebut dengan perang yang tak kunjung usai serta krisis ekonomi yang semakin memburuk. Hal yang sama dirasakan Faiza Al-Nour, seorang perempuan berusia 50 tahun yang mengungsi dari Khartoum selatan sejak Juni 2023. Ia mengungkapkan bahwa kesulitan ekonomi telah membuatnya tidak mampu mempersiapkan Ramadan seperti dulu.
Dengan keterbatasan yang ada, Faiza hanya bisa menyangrai satu kilogram biji kopi untuk dikonsumsi selama Ramadan karena ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli lebih banyak. Baginya, ini bukan sekadar kehilangan barang, tetapi juga kehilangan kebiasaan dan tradisi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan.
Krisis yang dihadapi warga Sudan juga telah diakui oleh lembaga-lembaga kemanusiaan dunia. Pada November 2024, Komisi Bantuan Kemanusiaan Sudan melaporkan bahwa 28,9 juta warga Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat perang. Kemudian, pada Januari 2025, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperbarui angka tersebut menjadi 30,4 juta.
Dampak dari perang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga menghancurkan sektor ekonomi Sudan secara keseluruhan. Pada Mei 2024, Kementerian Keuangan Sudan menyatakan bahwa sektor-sektor utama di negara tersebut telah lumpuh. Ekspor terhenti, mata uang mengalami devaluasi drastis, dan pendapatan negara anjlok hingga 80 persen. Sejak pernyataan tersebut dikeluarkan, tidak ada informasi terbaru mengenai bagaimana perang terus mempengaruhi perekonomian negara.
Selain menghentikan arus barang impor, konflik juga menghambat distribusi hasil pertanian lokal, memperburuk ketahanan pangan di Sudan. Abdul-Qadir Abdoun, seorang anggota Serikat Petani Sudan Utara, menjelaskan bahwa banyak hasil panen yang akhirnya terbuang sia-sia karena petani tidak dapat membawa produk mereka ke pasar.
Ia mencontohkan musim panen mangga tahun lalu, ketika hasil panen di beberapa daerah harus dibiarkan membusuk karena para petani tidak dapat mengirimkannya ke pasar utama. Selain itu, panen kentang tahun ini juga mengalami masalah serupa. Akibat biaya transportasi yang melonjak, petani hanya dapat menjual produk mereka secara lokal dengan harga yang terlalu rendah untuk menutup biaya produksi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perang bukan hanya merusak fisik kota-kota di Sudan, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian jutaan orang. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan penuh berkah dan kebersamaan kini berubah menjadi masa sulit bagi banyak keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah konflik yang belum menemukan titik terang.
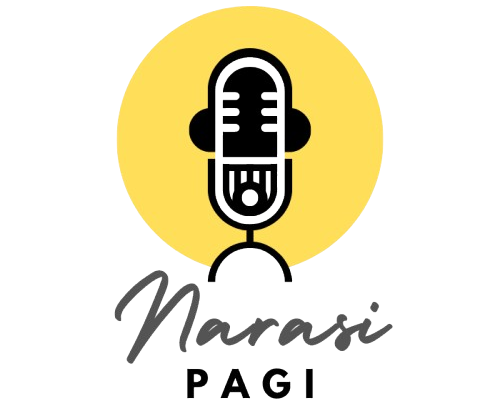




More Stories
600 Hektare Sawah di Demak Terendam Banjir, BNPB Lakukan Upaya Penanganan
Perpanjangan Kerja Sama Pengelolaan IPAL Australia di Palembang hingga 2028
Kementerian Agama Luncurkan E-Book Bimbingan Manasik Haji dan Umrah untuk Kemudahan Jamaah